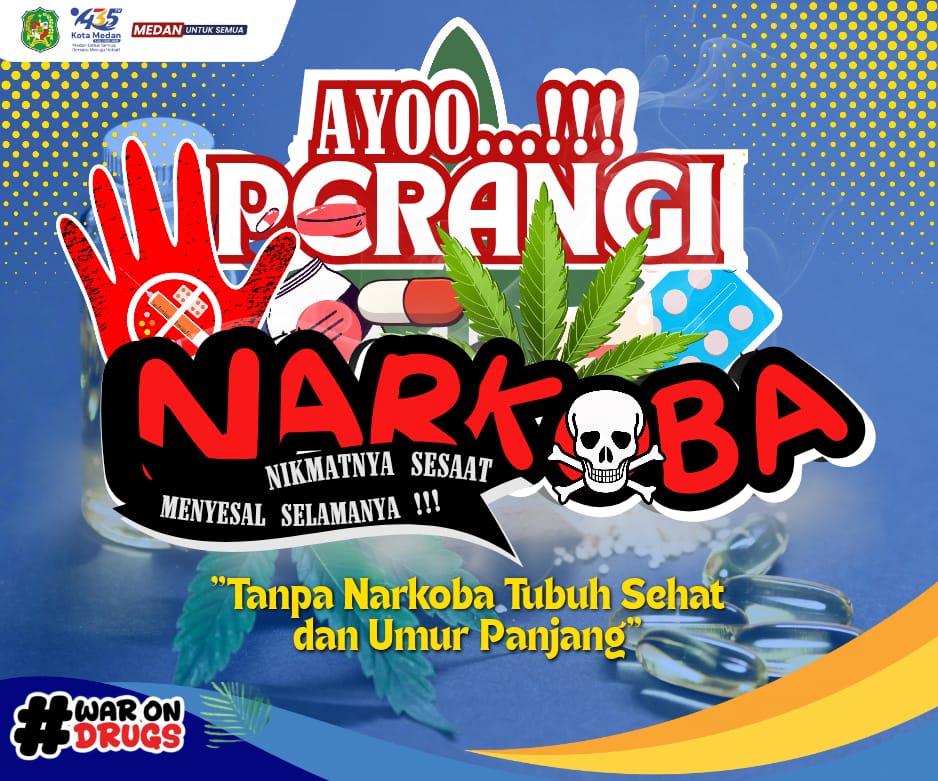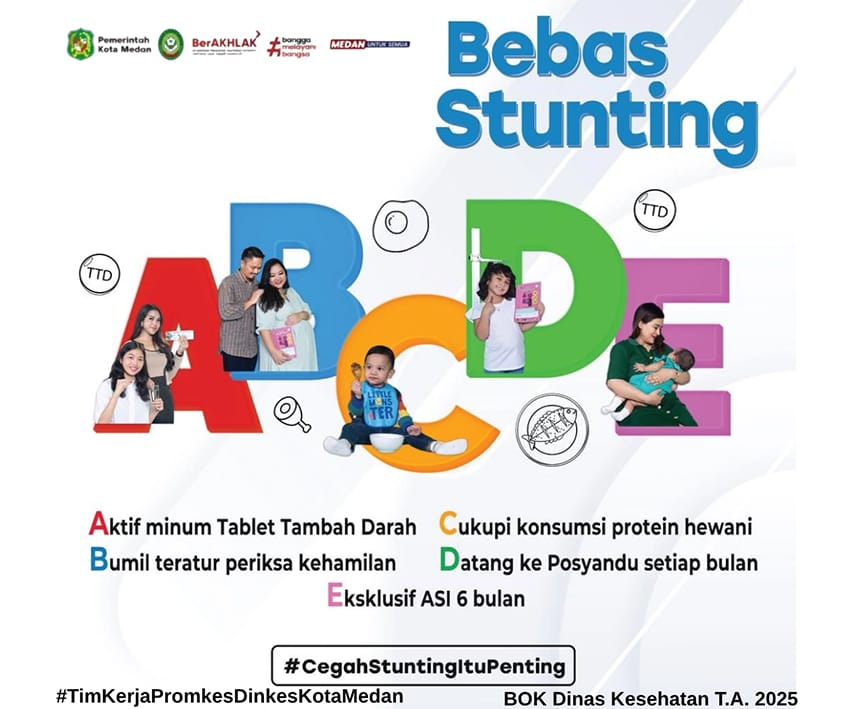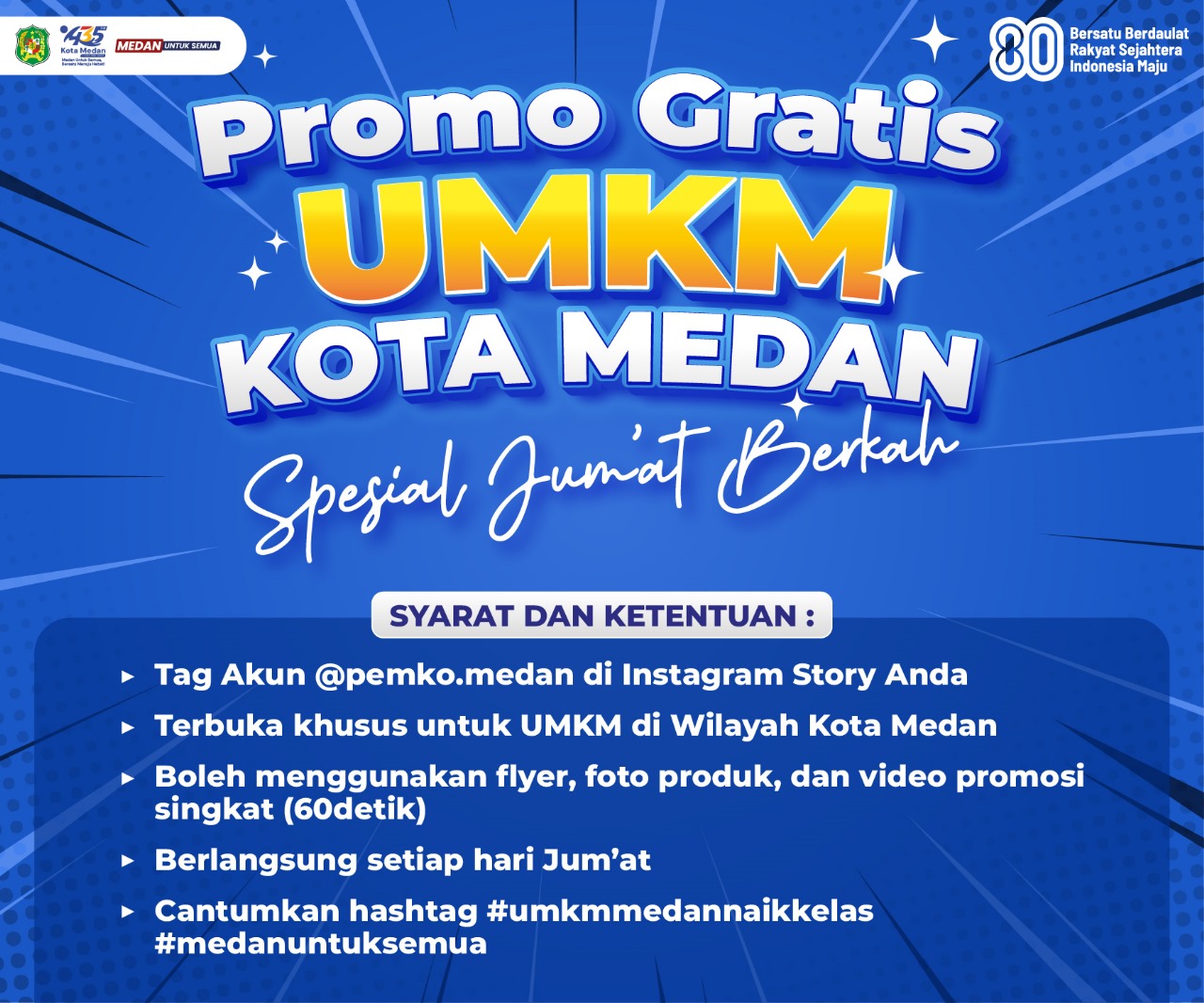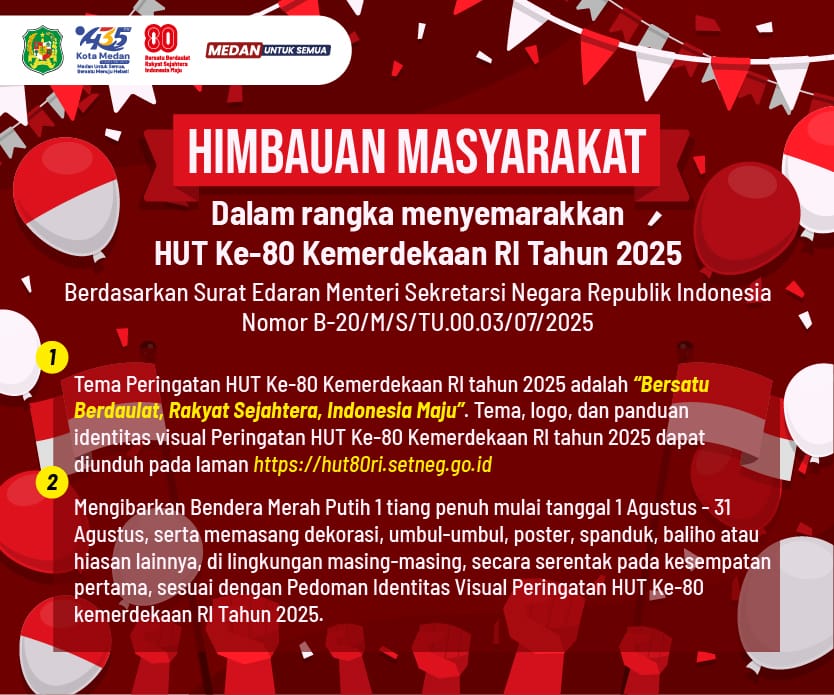Oleh: Rizal Tanjung
Tulisan ini merupakan kritik tajam terhadap pemahaman dan penggunaan yang keliru atas falsafah “batang tarandam” dalam tulisan Jacob Ereste yang berjudul “Seni dan Budaya Kita Seperti Batang Tarandam Yang Harus Diangkat oleh Fadli Zon”. Falsafah “batang tarandam” yang bersumber dari khazanah adat Minangkabau justru memiliki makna filosofis yang positif, yakni potensi tersembunyi, kematangan, dan kesabaran dalam menanti momentum kemunculan. Namun, dalam tulisan Ereste, falsafah tersebut disalahartikan menjadi simbol keterpurukan dan keterbenaman seni dan budaya nasional. Dengan membandingkan makna asli dengan penggunaannya yang keliru, tulisan ini mengungkap reduksi kultural, fatalisme retoris, dan problematika elitis dalam pandangan Jacob Ereste terhadap kesenian Indonesia.
- Pendahuluan: Ketika Falsafah Lokal Direduksi Secara Retoris
Dalam lintasan sejarah budaya Indonesia, istilah dan perumpamaan dari falsafah lokal memegang peran penting dalam menstrukturkan pandangan dunia masyarakat. Salah satu falsafah yang kaya makna dan berasal dari Minangkabau adalah “batang tarandam”—sebuah metafora yang menggambarkan kekuatan yang tersembunyi, ketabahan dalam diam, serta kematangan dalam kesabaran.
Namun, tulisan Jacob Ereste mencoba menggiring istilah ini ke dalam narasi yang salah arah: ia menyamakan “batang tarandam” dengan seni dan budaya Indonesia yang dianggap “mati suri”, terabaikan, dan perlu “diangkat kembali” oleh tokoh tertentu. Dalam hal ini, terjadi distorsi semantik dan pengkerdilan makna yang sangat berbahaya, baik bagi pembaca awam maupun bagi wacana kebudayaan nasional.
- Makna Falsafah “Batang Tarandam” dalam Kebudayaan Minangkabau
Secara harfiah, batang tarandam berarti batang kayu yang terendam di dalam air. Namun secara filosofis, ia mengandung nilai yang mendalam:
Potensi tersembunyi: ia tetap kuat meski tak terlihat di permukaan.
Kesabaran: ia menunggu saat tepat untuk muncul.
Kematangan: pengalaman dan waktu membuatnya lebih kokoh.
Dalam praktik sosial budaya Minangkabau, istilah ini sering digunakan untuk:
Calon penghulu adat yang belum muncul ke permukaan.
Individu cerdas yang belum bicara banyak tapi dalam diamnya menyerap ilmu.
Seniman yang berkarya diam-diam namun memiliki kekuatan artistik tinggi.
Dengan demikian, “batang tarandam” adalah simbol harapan dan kekuatan laten, bukan lambang keterpurukan atau kematian kultural.
- Penyimpangan Retoris dan Reduksi Kultural dalam Tulisan Jacob Ereste
Jacob Ereste, dalam artikelnya, menyatakan:
“Seni dan budaya yang mengusung nilai-nilai moral sebagai ekspresi dari spiritual akan segera punah…”
“Mungkinkah kondisi kesenian dan kebudayaan kita seperti yang dimaksud oleh Ninik Mamak dari semiotika batang tarandam itu?”
Dalam kalimat-kalimat ini, terlihat jelas bagaimana falsafah lokal dijadikan alat retoris untuk memperkuat narasi pesimistis dan fatalistik tentang kebudayaan Indonesia. Ini adalah bentuk penyalahgunaan makna filosofis, yang mengaburkan optimisme batang tarandam sebagai kekuatan tersembunyi, menjadi lambang keterpurukan yang pasif dan harus “diselamatkan”.
Ini bukan saja kesalahan interpretatif, tetapi kekeliruan epistemik, karena:
Menggunakan falsafah lokal di luar konteks budayanya.
Menjadikan istilah yang semestinya positif sebagai pembenaran untuk wacana peluruhan budaya.
Menganulir agensi kreatif seniman dan pelaku budaya kontemporer.
- Budaya Bukan Entitas Mati: Bantahan atas Konsep “Kematian Budaya”
Ereste menyatakan bahwa seni dan sastra Indonesia telah “mati suri”, “membeku”, “letoy”, dan “tak bergairah”. Ini adalah reduksi kasar atas dinamika kesenian Indonesia. Ia mengabaikan fakta:
Kesenian berkembang di ruang digital, media sosial, dan komunitas-komunitas.
Puisi, tari, teater, seni rupa, berkembang di luar kerangka institusi formal seperti Dewan Kesenian.
Budaya lokal hidup melalui transmisi baru: vlog budaya, festival rakyat, hingga seni performatif di ruang urban.
Ketika Jacob memaksakan dikotomi “hidup-mati” terhadap budaya, ia gagal memahami bahwa budaya adalah proses, bukan benda. Ia bukan artefak yang bisa “diangkat” lalu “dipamerkan”, tetapi denyut kehidupan yang diperbarui terus-menerus oleh rakyatnya.
- Problem Elitis: Menggantungkan Kebangkitan Budaya kepada Figur Politik
Jacob menyimpulkan:
“Inilah sesungguhnya pekerjaan berat dan serius yang perlu diatasi oleh Dr. Fadli Zon, selaku Menteri Kebudayaan…”
Menggantungkan kehidupan seni dan budaya kepada satu tokoh politik adalah kesalahan pandangan yang paternalistik. Budaya bukanlah objek intervensi kekuasaan, tetapi tumbuh dari partisipasi masyarakat. Penokohan semacam ini mengerdilkan agensi kolektif seniman, komunitas, dan rakyat dalam membentuk arah kebudayaan bangsa.
- Penutup: Saatnya Menghargai Falsafah Lokal dengan Benar
“Batang tarandam” adalah falsafah hidup yang luhur. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan, martabat, dan kematangan tidak harus selalu ditunjukkan secara bising. Ia bukan simbol keterbenaman, tetapi lambang potensi luhur yang sedang bersiap muncul. Menjadikannya sebagai simbol keterpurukan budaya adalah penghinaan terhadap makna lokal itu sendiri.
Jacob Ereste telah keliru. Dan kita wajib mengoreksi kekeliruan semacam ini agar wacana kebudayaan Indonesia tetap berpijak pada penghormatan terhadap nilai lokal, keberdayaan masyarakat, dan optimisme kultural yang progresif.
Untuk memahami falsafah “batang tarandam” Jacob Ereste perlu membaca buku:
Navis, A.A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Gramedia.
Bahar, S. (2002). Falsafah Adat Minangkabau. Padang: CV. Angkasa Raya.
Ratna, N. K. (2010). Metodologi Kajian Budaya dan Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maier, H. M. J. (1995). Seni dan Budaya dalam Perubahan: Dari Tradisional ke Digital. Leiden: KITLV.
Sumatera Barat 2025
Red